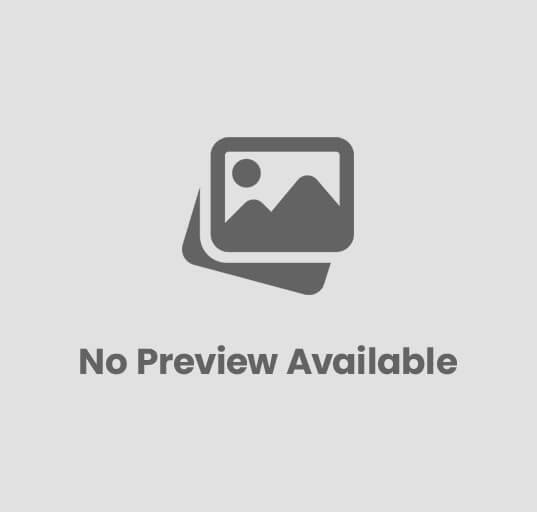
Menjalin Keamanan Ekologi melalui Penataan Tambang Ilegal
Oleh: Gendhis Sathiti *)
Di balik jargon lestari, pertambangan tanpa izin (PETI) telah lama menjelma luka terbuka di bentang alam Indonesia: merampas pendapatan negara, merusak hutan, dan memicu konflik horizontal. Dalam beberapa pekan terakhir, geliat kolaborasi antarlembaga—dari Kepolisian Daerah hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—menunjukkan pemerintah bergerak dari pola “pemadam kebakaran” menuju strategi tata kelola berbasis pencegahan, legalisasi, dan penegakan hukum berlapis. Pendekatan yang ditempuh layak diapresiasi sebagai ikhtiar merekonsiliasi kepentingan ekologis, ekonomi lokal, serta kedaulatan negara atas sumber daya alam.
Langkah konkret terlihat di Maluku Utara ketika anggota DPD RI Hidayatullah Sjah berdialog dengan Kapolda Irjen Pol Waris Agono. Kapolda Waris menjelaskan, penertiban PETI di Halmahera Selatan difokuskan pada legalisasi melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ia menyebut model ini solusi jangka panjang karena membuka kanal penerimaan negara, memungkinkan pengawasan ramah lingkungan, dan memutus rantai rente. Pendekatan itu tidak sekadar membubarkan tambang ilegal, melainkan menghadirkan negara sebagai pelindung hak nafkah masyarakat kecil—yang selama ini bergantung pada mendulang ore (bijih)—tanpa menormalisasi perusakan hutan.
Di Jakarta, KPK menghimpun Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan lembaga lain guna membahas perbaikan tata kelola nasional. Ketua KPK Setyo Budianto memaparkan hasil kajian soal karut-marut perizinan, tumpang‐tindih lahan, serta rendahnya kepatuhan finansial pelaku usaha; temuan tersebut kini menjadi agenda bersama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai integrasi data IPPKH di kawasan hutan sebagai kunci menutup celah manipulasi izin. Sementara Dirjen Minerba Tri Winarno menggarisbawahi penyisiran izin usaha pertambangan dari 12.500 menjadi 4.250 yang berstatus “clear and clean”, seraya menegaskan bahwa platform digital MODI, MOMI, e-PNBP, dan SIMBARA memampukan pengawasan berbasis big data real-time alih-alih hanya bertumpu pada patroli fisik.
Sinergi dilengkapi peran Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretaris Menteri BKPM Heldy Satrya Putera menjabarkan rekomendasi KPK: validasi seluruh perizinan, fasilitasi investor yang kesulitan, percepatan proses, dan pengawasan ketat sampai pencabutan izin jika menyimpang. Ia menekankan koordinasi pusat-daerah agar tak ada “zona abu-abu” yang kerap dimanfaatkan PETI—terutama setelah kewenangan perizinan dipusatkan melalui UU Cipta Kerja.
Meski terobosan kian nyata, pengamat mengingatkan bahwa tantangan masih menganga. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai PETI sebagai masalah struktural akibat koordinasi lemah dan pembiaran; di banyak wilayah, kewenangan sudah ditarik ke pusat tetapi kapasitas pengawasan belum sepadan sehingga tambang ilegal bermunculan. Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menambahkan, laporan lapangan kerap mentok di lingkaran oknum dan mengapresiasi operasi Bareskrim di Samboja—dekat Ibu Kota Nusantara—sebagai bukti negara tak pandang bulu.
Dari kacamata etika lingkungan, legalisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)–Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mencerminkan prinsip keadilan keterlibatan: negara tidak sekadar menutup tambang ilegal, tetapi membuka hak akses legal bagi penambang kecil agar tetap memperoleh nafkah tanpa merusak ekosistem. Masyarakat diajak berpartisipasi secara sah, sehingga relasi negara–warga bersandar pada perlindungan, bukan pemaksaan.
Di sisi lain, digitalisasi tata kelola—melalui platform MODI, MOMI, e-PNBP, dan SIMBARA—menjawab tuntutan keadilan prosedural. Data produksi, koordinat tambang, hingga kewajiban finansial tercatat transparan dan akuntabel, memutus ruang gelap praktik rente. Warga, pemda, dan pusat sama-sama bisa mengawasi, menegakkan hukum, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Apabila pendekatan legal-transformasional ini diiringi edukasi good mining practice, rehabilitasi berbasis ekonomi hijau, dan dashboard data yang juga dikonsumsi masyarakat desa, maka penindakan dan pencegahan bersinergi. Hasil akhirnya bukan hanya lanskap yang pulih, tetapi juga ketahanan ekonomi lokal—karena tambang legal diwajibkan merevegetasi lahan, menyisihkan dana reklamasi, dan menumbuhkan usaha turun-temurun yang berkelanjutan.
Bayangkan beberapa tahun ke depan: tambang-tambang rakyat yang telah berizin rutin melakukan revegetasi, penerimaan negara meningkat, dan anak-anak penambang kembali bersekolah karena orang tua mereka bekerja secara legal dan berpenghasilan layak. Pada titik itu, strategi pemerintah tidak sekadar menekan kemiskinan struktural, tetapi juga memulihkan moralitas ekologis kita sebagai bangsa—menegaskan bahwa kesejahteraan manusia dan kelestarian alam bisa berjalan beriringan.
Menggabungkan kepastian hukum, keterbukaan data, dan partisipasi publik, upaya memberantas PETI bergerak dari retorika menjadi gerakan nasional: satu langkah besar menata ulang hubungan manusia dengan bumi. Ketika legalisasi IPR–WPR berpadu dengan pengawasan digital dan edukasi lingkungan, ekologi yang lestari dan ekonomi yang adil tak lagi menjadi tujuan abstrak, melainkan capaian konkret yang dirasakan masyarakat di garis terdepan.
Keberhasilan skema ini tentu mensyaratkan kolaborasi lintas sektor yang konsisten—dari aparat penegak hukum yang sigap menindak pelanggaran, pemerintah daerah yang aktif mengawasi, hingga perguruan tinggi dan LSM yang memproduksi riset atas dampak ekologis dan sosial. Begitu pula perbankan dan BUMN harus hadir memberi akses pendanaan hijau agar penambang rakyat mampu beralih ke praktik ramah lingkungan tanpa terbebani biaya tinggi. Hanya dengan jejaring kolaboratif yang utuh, transformasi tambang ilegal menjadi tambang rakyat berkelanjutan akan bertahan melewati pergantian program dan periode pemerintahan.
*) pegiat isu lingkungan
Post Comment